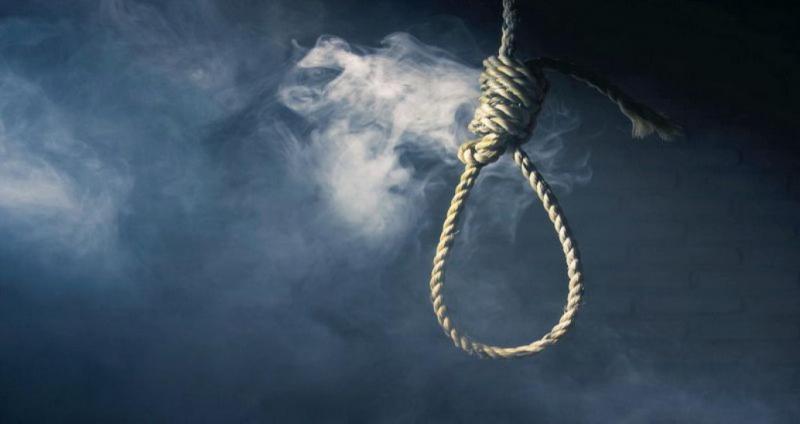Belajar Filsafat di Era Digital: Mencari Tuhan Lewat Platform Medsos?

Dulu, mencari Tuhan atau memahami pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup membutuhkan waktu berjam-jam di perpustakaan yang berdebu atau sudut-sudut masjid yang sunyi. Kini, yang kita butuhkan hanyalah ponsel pintar dan jaringan internet. Hanya dalam 60 detik, konten-konten di TikTok atau YouTube dapat memperkenalkan kita pada Sokrates, Rumi, dan Plato.
Begitulah wajah baru “ngaji”, istilah tradisional di Indonesia untuk studi atau pembelajaran agama. Namun, ngaji agama masa kini tidak lagi hanya terjadi di pesantren, universitas, atau lingkaran diskusi (halaqah), melainkan telah terjadi secara daring, dalam format video vertikal, yang sering kali diringkas menjadi konten padat. Pertanyaannya adalah: apa yang sebenarnya kita peroleh—dan mungkin juga hilang—ketika kita mencari Tuhan lewat layar?
Dari Masjid ke Algoritma
Jujur saja, filsafat dan teologi tidak pernah menjadi “konten yang mudah”. Topik tersebut lambat, rumit, dan sering menuntut kesunyian, keheningan, dan perjuangan. Namun, di dunia TikTok dan Instagram Reels, misalnya, kompleksitas sering kali dipadatkan. Pertanyaan-pertanyaan mendalam seperti “Apakah kehendak bebas itu ada?” atau “Apa hakikat Tuhan?” kini disajikan dalam semburan 30-60 detik.
Namun, yang mengejutkan, format demikian tampaknya berhasil, setidaknya dalam membuat orang tertarik. Seluruh generasi menemukan filsuf Islam seperti al-Farabi, Ibn Sina, al-Ghazali, dan bahkan tokoh Barat seperti Emerson dan Thoreau, sering kali melalui video yang memadukan referensi budaya pop dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam.
Seorang kreator mungkin berkata, “Ibn Arabi sama sekali tidak akan setuju dengan akhir film Marvel itu,” dan tiba-tiba, algoritma tersebut memberi kita klip tentang metafisika, mistisisme, dan ontologi Islam. Dengan cara ini, TikTok, YouTube, atau yang lainnya telah menjadi semacam halaqah digital, tempat pertanyaan-pertanyaan yang dulunya disediakan untuk buku-buku tua kini menjadi meme dan didiskusikan oleh para remaja sambil menyeruput kopi.
Tentu saja, ada sisi buruk dari semua ini. Filsafat—dan juga teologi—tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi seperti popcorn. Filsafat membutuhkan perhentian, refleksi, kontemplasi, percakapan, keraguan, dan kontradiksi. Namun, algoritma mengunggulkan kejelasan, kecepatan, dan penyederhanaan yang berlebihan. Algoritma tidak menyukai ambiguitas. Namun, ambiguitas justru merupakan tempat sebagian besar pertumbuhan spiritual dan filosofis terjadi.
Masalahnya bukanlah medsos “terlalu dangkal” untuk ide-ide besar, tetapi platform-platform medsos tersebut cenderung lebih menyukai kepastian daripada perenungan dan permenungan. Sebuah video berjudul “Bukti Tuhan Ada” kemungkinan akan lebih baik daripada video berjudul “Mengapa Kita Masih Bertanya”.
Namun, banyak anak muda yang memulai perjalanan filosofis mereka di sini, bukan mengakhirinya. Klip berdurasi 20 detik tentang Rumi mungkin membuat seseorang mengunduh buku puisinya. Sebuah unggahan tentang al-Ghazali mungkin memicu pencarian Google yang mendalam tentang Ihya Ulum al-Din. Dalam hal ini, meskipun bukan rumah, medsos dapat bertindak sebagai pintu.
Scroll and Soul: Risiko Spiritualitas Digital
Tetap saja, ada yang aneh tentang mencari hal ihwal transenden melalui layar yang dirancang untuk membuat kita tetap terpikat. Platform yang sama yang memberi kita refleksi tentang cinta ilahi juga mengetahui kebiasaan berbelanja dan membuat kita konsumtif. Ada ironi di sini: mencoba melepaskan diri dari ego dengan menggunakan alat yang paling berpusat pada ego di abad ini.
Filsafat digital berisiko menjadi apa yang disebut sebagian orang sebagai “spiritualitas estetika”, di mana gagasan “mencari makna menjadi lebih penting” daripada benar-benar melakukannya. Seseorang dapat mengutip Nietzsche tanpa bergulat dengan keputusasaan, atau memposting ulang gazal Rumi tanpa pernah jatuh cinta.
Ini bukanlah masalah baru. Bahkan dalam tradisi Islam klasik, para cendekiawan memperingatkan tentang ‘ilm bila ‘amal (pengetahuan tanpa tindakan). Di era digital, peringatan ini terasa lebih mendesak dari sebelumnya.
Kendati begitu, terlepas dari semua kekhawatiran ini, sesuatu yang indah sedang terjadi. Platform seperti YouTube atau TikTok menciptakan bentuk literasi spiritual yang tidak biasa. Kaum muda yang mungkin tidak pernah membuka buku teks filsafat kini bertanya pada diri sendiri: Apa itu jiwa? Apakah Tuhan hanyalah proyeksi manusia? Apa yang sebenarnya dimaksud al-Hallaj ketika ia berkata “ana al-Haqq”?
Pertanyaan-pertanyaan demikian penting. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin dimulai dengan meme, tetapi dapat berakhir pada transformasi signifikan. Lagi pula, banyak pencari hebat dalam sejarah memulai dengan pertanyaan kecil yang tumbuh seperti benih.
Apa yang ditawarkan era digital—jika digunakan dengan bijak—adalah akses. Bukan hanya akses ke informasi, melainkan juga ke rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu, jika dipupuk, mengarah pada pendalaman dan kedalaman.
Jadi, dapatkah kita benar-benar menemukan Tuhan melalui YouTube atau TikTok? Mungkin tidak sepenuhnya. Akan tetapi, kita mungkin menemukan rasa lapar akan Tuhan: pertanyaan-pertanyaan yang membawa kita lebih dekat. Ruang digital memang berisik, tetapi juga mencerminkan jiwa modern: terfragmentasi, bergerak cepat, dan bersifat pencarian.
Filsafat di era digital tidak lagi tentang jawaban, melainkan lebih tentang pantikan dan undangan. Filsafat adalah tentang menanamkan pemikiran yang bertahan setelah konten singkat berakhir. Filsafat semacam itu tentu tidak dapat menggantikan studi mendalam, tetapi dapat menjadi percikan yang membuat seseorang membuka buku, bergabung dalam komunitas, atau sekadar duduk diam dan bertanya, “Siapakah aku sebetulnya?”