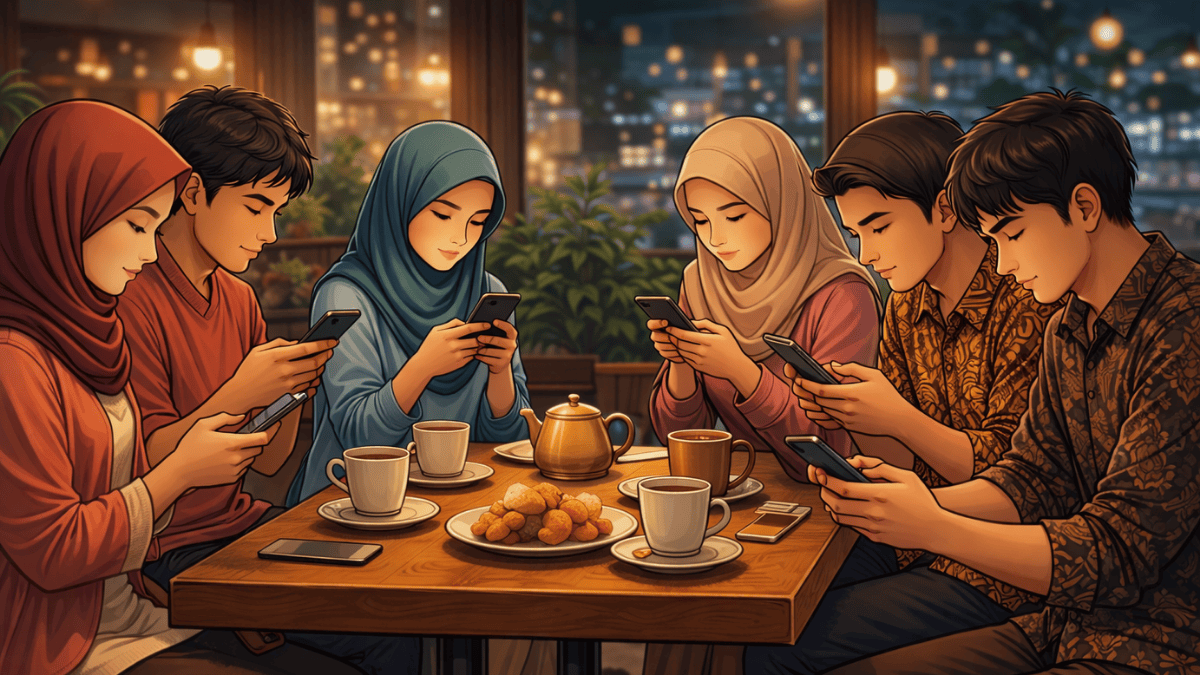Tafsir Ketaatan Ulil Amri antara Salafisme dan Muhammadiyah

Dalam tradisi pemikiran Islam, ketaatan kepada ulil amri selalu menjadi tema sentral dalam perdebatan tentang hubungan agama dan kekuasaan. Cara umat Islam memahami konsep ketaatan tidak hanya menentukan sikap keagamaan personal, tetapi juga membentuk orientasi politik, etika kewargaan, dan posisi umat dalam ruang publik. Karena itu, tafsir ketaatan ulil amri tidak pernah bersifat netral; ia selalu berkelindan dengan pandangan teologis, metodologis, dan konteks sosial yang melahirkannya.
Dalam hal ini, ayat “Ati‘ullāh wa ati‘ur-rasūl wa ulil amri minkum” (QS. an-Nisā’: 59) kerap menjadi rujukan utama dalam wacana relasi Islam dan kekuasaan khususnya terkait ketaatan terhadap ulil amri. Namun, sebagaimana diingatkan Fazlur Rahman, teks suci tidak pernah berbicara dalam ruang hampa; ia selalu ditafsirkan melalui kerangka ideologis dan kepentingan sosial-politik tertentu. Karena itu, perbedaan tafsir atas ayat ketaatan ini bukan sekadar perbedaan dalil, melainkan perbedaan visi tentang relasi agama, negara, dan warga.
Dalam tradisi Salafisme, ayat ini cenderung dipahami secara literal dan normatif-hierarkis. Ketaatan kepada ulil amri yang dimaknai sebagai penguasa dianggap kewajiban syar‘i selama tidak ada perintah maksiat yang eksplisit. Kritik terhadap penguasa sering dipandang sebagai ancaman stabilitas dan sumber fitnah.
Pandangan ini, sebagaimana dicatat Olivier Roy dalam “The Failure of Political Islam”, melahirkan depolitisasi umat yakni, agama dipisahkan dari agenda keadilan struktural, tetapi justru dilekatkan pada legitimasi kekuasaan.
Secara politis, tafsir ini menjadi problematik karena menyederhanakan makna ketaatan. Kekuasaan dipahami sebagai fakta yang harus diterima, bukan amanah yang harus diawasi.
Dalam bahasa Hannah Arendt, ketaatan semacam ini berisiko melahirkan “banalitas ketidakadilan”, ketika warga taat secara moral personal, tetapi pasif terhadap ketimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Agama, dalam posisi ini, kehilangan fungsi profetiknya sebagai kritik sosial.
Di sisi lain, Muhammadiyah menempuh jalan yang berbeda secara metodologis dan ideologis. Ketaatan kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak, sementara ketaatan kepada ulil amri bersifat kondisional, rasional, dan etis.
Pandangan ini sejalan dengan penegasan K.H. A.R. Fachruddin (Ketua PP Muhammadiyah 196-1990) yang menyatakan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kepatuhan buta, melainkan tanggung jawab moral.
Dalam konteks ini, istilah “ulil amri minkum” dipahami bukan hanya sebagai siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan yakni, secara adil, amanah, dan berpihak pada kemaslahatan publik.
Haedar Nashir menegaskan bahwa Islam Berkemajuan menolak dua ekstrem: politisasi agama dan depolitisasi umat. Ketaatan politik harus selalu diuji oleh nilai keadilan sosial dan konstitusi. Karena itu, kritik terhadap kebijakan negara yang koruptif, diskriminatif, atau menindas bukanlah pembangkangan, melainkan bentuk ketaatan substantif kepada tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah).
Pendekatan ini selaras dengan pandangan ilmuwan politik seperti Robert Dahl, yang menekankan bahwa demokrasi sehat mensyaratkan warga negara yang kritis, bukan sekadar patuh.
Dalam konteks Indonesia, tafsir Muhammadiyah atas ayat ketaatan mendorong lahirnya warga beriman yang aktif dalam ruang publik, menjaga keseimbangan antara stabilitas dan keadilan. Sebaliknya, tafsir ala Salafi berisiko melahirkan kesalehan individual yang steril dari tanggung jawab sosial-politik.
Tulisan ini merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual penulis untuk membangun diskursus keilmuan dan memperkuat ideologi Muhammadiyah.
Warga Muhammadiyah perlu memahami bahwa tafsir keagamaan memiliki konsekuensi politik. Tafsir yang memutlakkan ketaatan kepada penguasa berpotensi mengerdilkan peran umat sebagai subjek sejarah. Sebaliknya, tafsir yang menempatkan kekuasaan di bawah pengawasan etika ilahiah justru memperkuat demokrasi dan keadaban publik.
Islam tidak diturunkan untuk membungkam akal dan nurani. Ayat ketaatan justru menegaskan bahwa kekuasaan harus selalu berada dalam horizon pertanggungjawaban moral. Pada titik inilah Muhammadiyah mengambil posisi tegas yakni, taat kepada Allah dan Rasul, kritis terhadap kekuasaan, dan setia pada cita-cita keadilan sosial. Sebab, dalam politik kebangsaan, ketaatan sejati bukanlah kepatuhan tanpa nalar, melainkan keberanian menjaga amanah demi kemanusiaan. [AA]