
Fenomena Bunuh Diri dan Absurditas Hidup di Era Modern
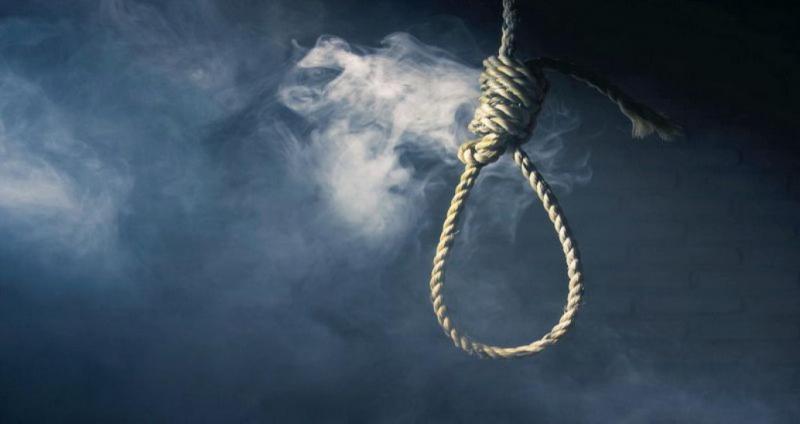
Kasus di dunia kian meningkat jumlahnya. Berdasarkan data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), terdapat sekitar 746 ribu kasus kematian akibat bunuh diri di seluruh dunia. Dari jumlah itu, Indonesia diperkirakan menyumbang 4.750 kasus bunuh diri terus saja terjadi di Indonesia. Dari angka tersebut, tidak sedikit yang berasal dari kalangan mahasiswa.
Terbaru, seorang Mahasiswi UIN Surakarta yang juga pengidap bipolar meninggal (17/10) dunia usai melompat dari lantai lima rooftop di kampusnya. Mahasiswa yang seharusnya berada pada usia produktif, justru malah kehilangan alasan untuk melanjutkan hidupnya.
Pertanyannya, mengapa hal demikian bisa terjadi?
Seorang filsuf eksistensialis, Albert Camus mengatakan bahwa bunuh diri adalah masalah filosofis yang paling serius. Camus menganggap bahwa bunuh diri bisa terjadi karena manusia tidak menemukan lagi apa tujuan dan makna dari hidupnya. Keputus-asaan akan pencarian tersebut pada akhirnya membawa seseorang kepada yang biasa disebut oleh Camus sebagai “Absurditas”
Ketika seseorang sudah terjebak pada absurditas, menurut Camus ada dua cara untuk menghadapinya, yaitu bunuh diri atau memberontak. Ia membagi bunuh diri menjadi dua, yakni bunuh diri fisik dan bunuh diri filosofis. Bunuh diri fisik berarti mengakhiri hidup secara sengaja dengan menghilangkan nyawanya. Sedangkan bunuh diri filosofis bisa dikatakan seperti lompatan iman yang dilakukan oleh Kierkegaard, yaitu memasrahkan dirinya pada sesuatu yang dianggap lebih tinggi dan irasional.
Namun, bagi Camus jawaban yang paling tepat untuk menghadapi hal tersebut adalah dengan memberontak. Dalam karyanya Mitos Sisifus, dia menggambarkan seorang sisifus yang terus mendorong batu menaiki bukit yang tinggi, walaupun akhirnya batu itu menggelinding kembali ke bawah karena lemahnya sisifus tadi. Namun, sisifus itu tidak pernah menyerah, dia terus mencoba dan mencoba walaupun akhirnya sia-sia juga.
Jika dikaitkan dengan kehidupan mahasiswa, kita bisa melihat bahwa mereka diliputi oleh banyak tekanan. Tekanan tersebut biasa dari tuntutan akademik, ekonomi, keluarga, bahkan lingkungan secara luas. Ketika seorang mahasiswa dinilai hanya dengan nilai IPK atau capaian karier mereka.
Selain itu mereka juga harus hidup di tengah arus media sosial yang sangat cepat. Dimana mereka bisa menjangkau orang lain di seluruh penjuru dunia yang hanya menampilkan kesempurnaan di layar kaca tersebut.
Hal ini bisa membuat mahasiswa makin merasa kalah dan tertinggal, sehingga dirinya terjebak dalam ketidakjelasan akan masa depan. Ditambah lagi jika mereka mendapatkan lingkungan yang toxic, lingkungan yang sama sekali tidak mendukung dan menghargai, bahkan meremehkan akan perjuangan mereka. Hal-hal demikian bisa membuat mahasiswa merasa terjebak dalam penderitaan yang terus mengekang. Sehingga dirinya melihat bahwa hidup hanyalah kesia-siaan, tidak tahu lagi untuk apa hidupnya terus berjalan.
Rentetan penderitaan tersebut, menurut Camus, sebenarnya bisa disiasat dengan konsep “bayangkan sisifus bahagia”. Konsep ini menekankan pada keyakinan akan datangnya kebahagiaan yang menunggu di depan meskipun berbagai penderitaan terus melanda.
Tujuan utama dari konsep ini adalah agar hidup terus diliputi secercah harapan semangat di antara bayangan kesia-siaan. Seseorang harus memberontak atas keadaan (penderitaan) yang meliputinya karena dengan itu akan menyadari bahwa ia mempunyai eksistensi berupa kebebasan untuk memaknai hidup tersebut.
Seseorang bisa menemukan makna hidupnya lagi melalui hal-hal kecil. Dirinya bisa mencari lingkungan yang baik untuk berkembang. Dengan kesadaran akan kebebasan yang dimiliki, ia bisa mencoba untuk melawan tuntutan-tuntutan yang mengekang tadi sesuai apa yang dia mau. Tidak perlu lagi melihat kesuksesan orang lain sebagai acuan.
Secara ideal mungkin hal-hal tersebut bisa dibayangkan dengan mudah. Namun tidak bisa dipungkiri, ada juga orang yang harus menjalani hidupnya dengan penderitaan yang lebih. Misalnya seorang pengidap penyakit mental, seperti yang dialami oleh mahasiswi UIN Surakarta tadi.
Bipolar adalah penyakit mental yang memiliki dua polar, yaitu manik dan depresif. Ketika dalam fase manik, seseorang akan merasa terlalu bahagia ataupun sekaligus terlalu berenergi. Sebaliknya, ketika dalam fase depresif akan merasa dunianya seperti gelap gulita, kosong, dan putus asa.
Kembali pada kasus mahasiswi tadi. Ia sempat menulis beberapa hal untuk menceritakan kondisinya yang sedang berjuang melawan sakitnya itu. Jika kita membaca tulisan-tulisan mahasiswi tersebut, akan terungkap bahwa dirinya sudah berusaha untuk tetap menjalani hidupnya dengan semangat dan bahagia. Namun apa daya, fase depresif akan senantiasa menyelimutinya dan para penyintas bipolar lainnya terutama ketika mereka ketika itu dirinya sedang berada dalam puncak keputus-asaanya.
Dari kasus ini kita mendapat banyak pelajaran, bahwa kesehatan mental sama sekali tidak boleh diremehkan. Dibalik senyum dan tawa mungkin ada perjuangan melawan luka yang tak pernah kita lihat. Kepedulian antar sesama diperlukan pada masalah ini. Seorang penyintas perlu untuk didengarkan, diberi semangat, dan harapan. Setidaknya dengan itu bisa membuat dirinya ingin hidup lebih lama lagi. Yang pasti, di tengah absurditas yang kita alami, ada satu hal yang perlu selalu untuk diyakini bahwa manusia selalu memiliki kemampuan untuk memberi arti, sekecil apa pun itu.






