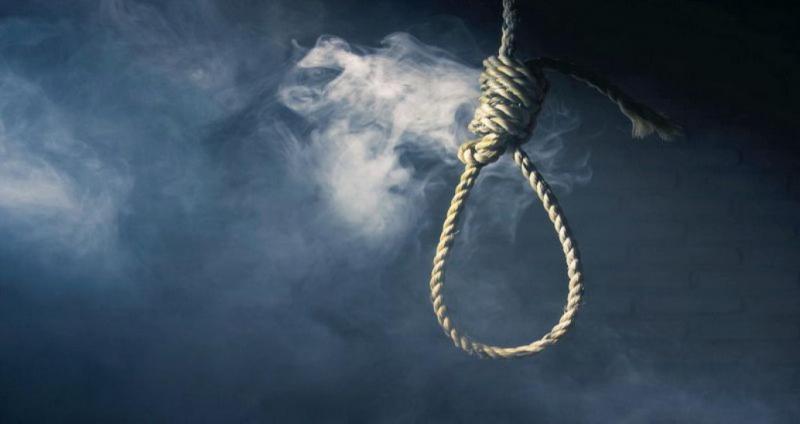Politik Fikih NU: Membaca Risalah Harian Syuriyah PBNU

Dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU), politik jarang tampil dalam bentuk ledakan. Tidak ada teriakan, tidak ada saling sindir di depan kamera, dan tidak ada pemecatan mendadak yang diumumkan pada konferensi pers darurat. Yang ada justru sebuah mekanisme yang berjalan tenang, pelan, namun memiliki daya ubah yang signifikan.
Fenomena terbaru terkait Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU (20/11/2025) ketika Pengurus Syuriyah memberikan tenggat tiga hari kepada Ketua Tanfidziyah, K.H. Yahya Cholil Staquf, adalah bukti bahwa NU tetap mempertahankan pola klasiknya: politik fikih, strategi menjatuhkan tanpa terlihat sedang menjatuhkan. Tidak selalu tampak kasar, tetapi setiap langkahnya punya illat, manath, dan qiyas yang membuat para santri senior geleng kepala sambil berucap, “Lah, ini kok mirip bab thalak bain, ya?”
Langkah Pengurus Syuriyah ini sederhana, bahkan tampak sepi: sebuah pernyataan tanpa nada tinggi, tanpa ancaman, tetapi penuh makna.
Di kultur NU, pernyataan semacam itu bukan sekadar imbauan administratif. Ia adalah penanda bahwa ada sesuatu yang serius, bahwa sebuah mekanisme etis sedang bekerja. Dan bahwa kekuasaan, dalam tradisi NU, tidak dikelola dengan logika menang-kalah, melainkan dengan bahasa moral dan tata tertib fikih.
Dalam literatur klasik fiqh siyasah, pengelolaan kekuasaan tidak boleh dilakukan melalui cara yang merusak tatanan sosial. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah menekankan bahwa setiap keputusan pemimpin harus memastikan bahwa masyarakat tetap stabil. Ibn Taymiyyah bahkan menyebut bahwa kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang paling sedikit mudaratnya bagi public.
Karena itu, pendekatan Pengurus Syuriyah sesungguhnya menyimbolkan prinsip dasar siyasah: teguran sebelum tindakan, moral sebelum hukuman, musyawarah sebelum pemecatan. NU tidak memecat secara langsung karena bagi mereka, keputusan yang terburu-buru dapat merusak marwah. AD/ART diperlakukan seperti nash syar’i, harus dijaga secara ketat. Sekali dilanggar, legitimasi organisasi melemah.
Jejak Historis: NU dan Konflik yang Diselesaikan dengan “Jalan Halus”
Pendekatan “menjatuhkan tanpa menjatuhkan” ini sesungguhnya bukan fenomena baru. Sejarah NU menyimpan sejumlah peristiwa serupa, konflik yang tidak meledak, tetapi diselesaikan melalui jalur sunyi yang penuh perhitungan;
Pertama, konflik PBNU–Masyumi (1940–1950-an). Ketegangan antara para kiai NU dan elit Masyumi berlarut-larut, tetapi tidak pernah pecah dalam bentuk pengusiran dramatis. Para kiai memilih keluar dari struktur Masyumi secara berangsur, melalui pernyataan-pernyataan halus yang pada akhirnya mendorong NU berdiri sebagai partai sendiri (1952). Proses “keluar pelan-pelan” itu menjadi teladan bagaimana NU menggunakan mekanisme tekanan moral alih-alih konflik terbuka.
Kedua, ketegangan K.H. Idham Chalid dan kubu kritis 1970-an. Pada masa Orde Baru, konflik kepemimpinan dalam NU sebenarnya cukup panas. Namun mekanismenya tidak berupa mosi tidak percaya. Para kiai mengerem ekspresi konflik dan memilih jalur Munas (Musyawarah Nasional) serta Musyawarah Kiai di Situbondo (1983). Lagi-lagi, mekanisme nushrah (teguran keras) mendahului hukm.
Ketiga, Konflik PBNU era 1999–2004. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid, ketegangan antara PBNU dan pihak internal berlangsung keras secara wacana, tetapi penyelesaian struktural tetap ditempuh melalui forum muktamar, bukan pemecatan langsung. Kritik disampaikan, teguran diberi, tetapi langkah-langkah formal tetap ditahan agar AD/ART menjadi rujukan tunggal.
Dalam tiga peristiwa tersebut, pola yang sama muncul, tekanan moral, bukan sanksi administratif. NU selalu memilih jalur yang menjaga wajah semua pihak.
Maka ketika Syuriyah hari ini memberi tenggat tiga hari, itu bukan tindakan baru, melainkan pola lama yang bekerja lagi. Tradisi yang diwariskan para kiai agar konflik tetap terkendali, tidak merusak ukhuwwah jama’ah. Dalam kacamata politik fikih, ini disebut tahwil al-mas’uliyyah, pergeseran tanggung jawab dari struktur atas ke personal
Jika seorang Ketua Tanfidziyah tidak merespons sesuai arahan Pengurus Syuriyah, maka tindak lanjutnya bukan lagi persoalan moral pribadi. Ini sudah memasuki wilayah siyasah syar’iyyah tingkat lanjut. Dalam konsep politik Islam klasik, pemimpin yang mengabaikan otoritas moral lebih tinggi dapat dianggap kehilangan sebagian legitimasi adabiyyah (etika), meskipun secara administratif ia masih memegang jabatan.
Situasi seperti ini ibarat imam yang sujud terlalu lama: sah, tetapi dipertanyakan. Jemaah ingin salat berjalan, tetapi ingin juga kepemimpinan dijalankan dengan adab.
Jika kebuntuan berlanjut, PBNU sebagai “qadhi qudhah” (hakim tertinggi dalam struktur pemerintahan klasik) bisa turun tangan. Sejarah menunjukkan, langkah seperti; pembekuan jabatan, penunjukan pelaksana tugas, atau konferensi ulang adalah jalan yang pernah diambil PBNU dalam merespons kebuntuan organisasi daerah.
Dengan demikian, dinamika tiga hari bukan sekadar ultimatum. Ia adalah pembuka rangkaian mekanisme yang jauh lebih kompleks.
NU dan Politik Keheningan
Salah satu kekuatan terbesar NU adalah kemampuannya mengelola ketegangan internal tanpa kehilangan martabat. Politik dalam NU tidak pernah sepenuhnya merahasiakan ketegangan, tetapi juga tidak menjadikannya tontonan publik. Kekuatan NU justru ada pada kemampuan menjaga perbedaan tetap berada dalam ruang yang tidak melukai.
Dalam kultur NU, keheningan sering menjadi bahasa paling keras. Pernyataan pendek sering menjadi tanda bahwa pergolakan besar sedang berjalan. Tidak ada gebrakan suara tinggi, tetapi ada langkah-langkah yang membuat perubahan tidak terelakkan.
Mekanisme “menjatuhkan tanpa menjatuhkan” bukanlah strategi kekuasaan ala feodal, tetapi cara menjaga agar konflik tidak berubah menjadi perpecahan. NU sudah terlalu besar untuk hidup dalam pola politik konfrontatif. Maka tradisi fikih menjadi jalan tengah: mengatur konflik dengan etika, menunda keputusan keras sampai batas paling lembut, dan memberikan ruang kepada setiap pemimpin untuk keluar dengan kehormatan.
Kasus Pengurus Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah hari ini bukan sekadar soal perbedaan pandangan. Ia adalah potret bagaimana NU mempertahankan tradisinya dalam mengelola kekuasaan: tidak melalui gebrakan, tetapi melalui isyarat; tidak melalui sanksi eksplisit, tetapi melalui tekanan moral; tidak melalui pemecatan, tetapi melalui adab siyasah. NU mungkin tidak berisik. Tetapi langkah-langkahnya selalu sampai.
Dalam keheningan itulah, politik fikih NU menemukan relevansi dan kekuatannya: menjaga stabilitas, kehormatan, dan marwah organisasi dengan cara yang tak selalu terlihat, namun selalu terasa. Wallahu a’lam [AA]