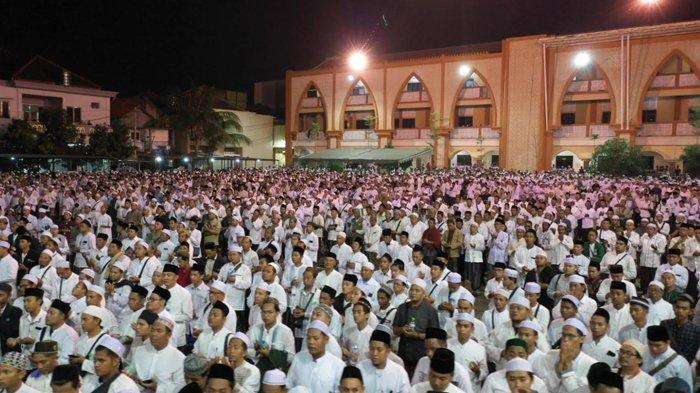
Apakah Surga dan Neraka Mesti Dipahami secara Harfiah?

Tak ada gagasan yang membentuk imajinasi manusia tentang kehidupan lebih kuat dibanding gagasan tentang surga dan neraka. Keduanya muncul di berbagai agama dan budaya, yang satu bersinar dengan janji serta harapan, sedangkan yang lain dibayangi ketakutan.
Selama berabad-abad, para seniman, penyair, dan pengkhotbah telah memberikan bentuk yang hidup pada dua tempat ini: tempat kebahagiaan dan cahaya abadi di satu sisi dan api, siksaan, serta kegelapan tak berujung di sisi lainnya. Namun, seiring perkembangan pemikiran manusia, kita dihadapkan pada pertanyaan yang mendesak, yakni haruskah surga dan neraka dipahami secara harfiah?
Pemaknaan harfiah inilah yang dipahami sebagian besar dari kita saat tumbuh dewasa. Surga, menurut ajaran agama, adalah sebuah tempat “di atas”, di mana jiwa-jiwa yang baik akan hidup selamanya.
Sebaliknya, neraka adalah dunia bawah yang terdapat kobaran api bagi mereka yang telah gagal secara moral maupun spiritual. Citra ini memiliki tujuan sosial dan etis. Ia memperkuat perilaku moral melalui harapan dan ketakutan, yaitu berbuat baiklah maka engkau akan diberi pahala atau berbuat jahatlah maka engkau akan menderita.
Kerangka pikir semacam itu telah mendorong kehidupan masyarakat selama berabad-abad, menyediakan struktur dan makna di dunia yang sering kali terasa kacau. Kendati begitu, pandangan literal juga menimbulkan masalah filosofis. Jika surga dan neraka adalah lokasi yang sebenarnya, di manakah keduanya?
Kosmologi abad pertengahan yang menempatkan surga di atas langit dan neraka di bawah bumi tidak lagi sesuai dengan alam semesta yang kita kenal sekarang, yakni meluas dan tampak nirbatas. Lebih lanjut, apa artinya mengalami hukuman abadi dalam sistem moral yang diatur oleh Tuhan yang konon penuh belas kasih?
Jika yang ilahi adalah kasih yang tak terbatas, bagaimana mungkin ia hidup berdampingan dengan siksaan yang tak terbatas? Ini bukan sekadar teka-teki teologis, melainkan juga menyentuh inti dari bagaimana kita membayangkan keadilan, belas kasih, dan tatanan moral itu sendiri.
Bagi banyak pemikir modern, surga dan neraka bukanlah tujuan literal, melainkan bahasa simbolis, sebuah metafora spiritual untuk keadaan eksistensial. Seorang sufi abad ke-13, Ibn Arabi, misalnya, menulis bahwa surga dan neraka adalah “cara persepsi” alih-alih tempat.
Baginya, surga adalah pengalaman jiwa akan kedekatan ilahi, sementara neraka adalah rasa sakit perpisahan. Keduanya tidak ada di langit atau di bawah tanah, melainkan di dalam diri.
Apa yang kita sebut “neraka” bukanlah hukuman yang dijatuhkan, melainkan konsekuensi batin dari keterasingan dari kebenaran ilahi. Dalam pengertian ini, surga dan neraka bukanlah kehidupan setelah kematian, melainkan cara hidup dan melihat masa kini.
Penafsiran ini sangat selaras dengan wawasan psikologis. Ketika orang menggambarkan sukacita cinta, kebaikan, dan kekaguman, mereka sering menggunakan bahasa-bahasa surga seperti cahaya, kedamaian, perluasan.
Ketika mereka menggambarkan rasa bersalah, kebencian, atau keputusasaan, mereka menggunakan bahasa-bahasa neraka seperti panas, sesak napas, pengap, sumpek, kurungan. Surga dan neraka, dengan demikian, mungkin merupakan tata bahasa simbolis yang melaluinya kesadaran manusia mengekspresikan pengalaman ekstrem.
Api neraka dapat mewakili intensitas penyesalan yang membara, sedangkan sungai-sungai surga mewakili aliran harmonis dalam batin. Namun, menolak literalisme tidak berarti mengabaikan surga dan neraka hanya sebagai “cerita”. Sebaliknya, ini berarti memahaminya sebagai topografi moral dan eksistensial, yaitu peta jiwa yang mengungkapkan betapa dalamnya pilihan kita membentuk kualitas eksistensial kita.
Menafsirkan keduanya secara metaforis bukan berarti melemahkan maknanya, melainkan justru memperdalamnya. Jika surga dan neraka ada di dalam diri kita, maka keselamatan dan kutukan tidak akan ditunda ke dunia lain atau dunia selanjutnya, sebab keduanya telah tersingkap dalam setiap tindakan belas kasih atau kekejaman yang kita lakukan di dunia (k)ini.
Pembacaan simbolis juga membuka pintu dialog antaragama. Meskipun doktrinnya berbeda, hampir semua tradisi berbicara tentang dua realitas yang kontras, satu selaras dengan harmoni, yang lain dengan keterputusan.
Dalam Buddhisme, misalnya, “alam neraka” adalah kondisi kesadaran yang didominasi oleh kebencian dan ketidaktahuan, sementara pencerahan mewakili pembebasan dari kondisi-kondisi ini.
Dalam Kekristenan, teolog seperti C. S. Lewis berpendapat bahwa “pintu-pintu neraka terkunci dari dalam”. Artinya, kutukan adalah keterasingan yang dipilih sendiri dari cinta. Paralel semacam itu menunjukkan bahwa gambaran surga dan neraka berfungsi lebih sebagai fenomenologi etis, yaitu cara puitis untuk menggambarkan perjumpaan jiwa dengan kebenaran atau ketiadaannya.
Namun, interpretasi literal dan simbolis tidak perlu saling dikontraskan. Kekuatan imajinasi religius justru terletak pada ambiguitasnya. Bagi orang beriman, gambaran surga dan hukuman yang gamblang menjadikan realitas moral yang abstrak menjadi konkret dan menggugah emosi.
Gambaran-gambaran itu justru dapat menerjemahkan kebenaran yang tak kasat mata menjadi gambaran yang dapat ditangkap oleh pikiran manusia. Tantangan muncul ketika kita lupa bahwa gambaran-gambaran ini adalah tanda-tanda yang menunjuk melampaui dirinya sendiri.
Pada akhirnya, apakah seseorang mengartikan surga dan neraka secara harfiah atau metaforis bergantung pada bagaimana ia memahami bahasa itu sendiri. Bahasa religius, tidak seperti deskripsi ilmiah, bersifat performatif: ia tidak sekadar menyatakan fakta, melainkan utamanya membentuk dunia.
Mengatakan “ada surga” berarti menegaskan bahwa kebaikan itu penting dan bahwa keadilan tidak akan lenyap dalam kehampaan. Mengatakan “ada neraka” berarti mengakui bahwa kejahatan memiliki konsekuensi dan bahwa kebebasan memiliki bobot tanggung jawab yang serius. Sekalipun alam ini tidak bersifat fisik, mereka tetap nyata secara moral, senyata cinta, penyesalan, dan kekaguman.
Jadi, mungkin pertanyaan yang lebih baik bukanlah di mana surga dan neraka berada, tetapi manusia macam apa yang kita lakukan, surgawi atau nerakawi. Jika tindakan kita mengarahkan kita menuju welas asih, kesadaran, dan cinta yang lebih besar, maka kita sudah berada, sampai taraf tertentu, di surga. Jika tindakan kita malah destruktif dan tak bertanggung jawab, kita merasakan api neraka di sini dan saat ini.




